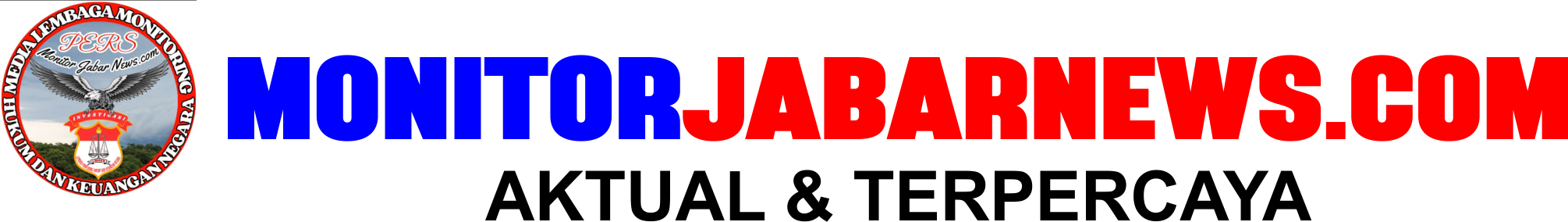Mochdar Soleman, S.IP., M.SI
Akademisi Universitas Nasional / Sekjen GP Nuku
Jakarta – Banjir bandang yang menghantam Sumatera beberapa hari lalu meninggalkan pemandangan yang tak mungkin dijelaskan sebagai kebetulan alam: ribuan batang kayu gelondongan terbawa arus, menumpuk di jembatan, permukiman, dan pinggir sungai. Kayu-kayu itu tidak tumbang karena angin. Mereka dipotong dengan rapi, dipersiapkan, dan jelas berasal dari aktivitas penebangan yang berlangsung jauh sebelum bencana itu tiba.
Fenomena ini bukan sekadar banjir. Ia adalah pengakuan tanpa kata bahwa negara telah kehilangan kendali atas hutannya sendiri. Dan lebih jauh lagi, bahwa hulu sungai di Sumatera bukan lagi ruang ekologis, akan tetapi menjadi medan perburuan ekonomi yang sarat kolusi.
Pemerintah bergerak sangat lamban. Baru bergerak setelah publik memviralkan foto-foto kayu gelondongan berserakan di aliran sungai setelah itu barulah muncul pernyataan pemerintah tentang perintah investigasi, pemanggilan menteri, dan klarifikasi dari kementerian kehutanan. Semua itu menegaskan satu hal bahwa negara hanya hadir ketika bencana sudah pecah, bukan ketika kerusakan sedang diproduksi.
Terlihat jelas narasi resmi berputar-putar yakni; kayu mungkin berasal dari pohon tumbang, dari hutan rakyat, dari kayu legal, dari aktivitas lama, dari banjir sebelumnya. Semakin banyak kemungkinan yang disebutkan, semakin jelas bahwa tak ada satu pun data yang benar-benar dipegang negara. Ketika institusi kehutanan tidak dapat membedakan mana kayu legal, ilegal, atau “tak bertuan”, itu bukan kelemahan administrative melainkan itu adalah indikator hilangnya kedaulatan ekologis.
Dan dalam situasi seperti ini, kayu gelondongan yang hanyut adalah bukti paling telanjang dari sebuah pertanyaan sederhana bahwa siapa sebenarnya yang menguasai hutan?
Jika ditarik dari hulu, banjir kayu Sumatera membuka fakta tentang jaringan aktor yang selama ini menguasai ruang ekologis dimana perusahaan kayu, operator pembalakan, pemilik alat berat, hingga elite lokal yang menjadi perantara dan semuanya terhubung oleh akses yang longgar, regulasi yang bocor, serta pengawasan yang memilih tutup mata. Hutan tidak rusak oleh satu aktor tunggal, melainkan oleh jaringan kepentingan yang dibungkus legalitas abu-abu.
Di sinilah masalah terbesar berada bahwa negara selama ini membangun sistem izin kehutanan yang membuka banyak pintu, tapi tidak menjaga satupun. Skema legalitas seringkali sekadar administrasi yang dapat dinegosiasikan, dimanipulasi, bahkan disulap menjadi legitimasi bagi operasi ekstraksi yang rakus. Ketika kayu gelondongan bisa keluar dari hulu tanpa terdeteksi, itu berarti sistem perizinan bukan hanya lemah akan tetapi sengaja dibiarkan longgar demi kepentingan tertentu.
Kita menyaksikan hutan yang dipreteli perlahan, lalu ketika banjir datang, kita hanya melihat jejak yang hanyut.
Dalam konteks yang lebih luas, banjir kayu Sumatera adalah akibat dari pembangunan yang salah arah. Hulu sungai diperlakukan seperti ruang ekonomi yang harus dieksploitasi, bukan sistem ekologis yang harus dijaga. Sebegitu mudahnya negara memberi izin, begitu liarnya ekspansi perkebunan dan kayu, dan begitu lemahnya penegakan hukum, hingga resapan air yang hilang menjadi tak terhindarkan.
Banjir itu hanyalah puncak dari deret panjang kerusakan ekologis “tutupan hutan menyusut, tanah kehilangan daya ikat, sungai tidak lagi mampu menampung hujan ekstrem, dan masyarakat hilir menjadi korban.”
Dan seperti biasa, negara selalu menyalahkan alam terlebih dahulu sebelum melihat ke cermin.
Kita membutuhkan lebih dari sekadar investigasi. Investigasi sering berakhir sebagai ritual politik untuk meredam opini publik. Kita butuh audit menyeluruh semua konsesi, semua izin PHAT dan APL, semua rantai distribusi kayu di wilayah hulu, dan terutama “siapa yang selama ini menikmati keuntungan dari pembukaan lahan.”
Kita membutuhkan keberanian negara untuk mengakui bahwa hutan telah menjadi arena transaksi kekuasaan. Tanpa pengakuan itu, pembenahan hanya akan menjadi kosmetik.
Banjir kayu Sumatera adalah sinyal keras bahwa ekologi kita berada di tepi krisis struktural. Jika negara terus menunda koreksi, maka bukan hanya kayu yang akan hanyut di sungai—tetapi juga masa depan ekologis kita.
Bencana ini seharusnya menjadi batas dimana “negara tak boleh lagi menjadi institusi yang datang terakhir, setelah kerusakan terjadi.” Karena pada akhirnya, hutan yang rusak adalah cermin dari negara yang absen. Dan setiap batang kayu yang hanyut adalah pengingat bahwa pembangunan yang tak peduli ekologi hanya menghasilkan satu hal “Bencana Yang Menunggu Giliran.”