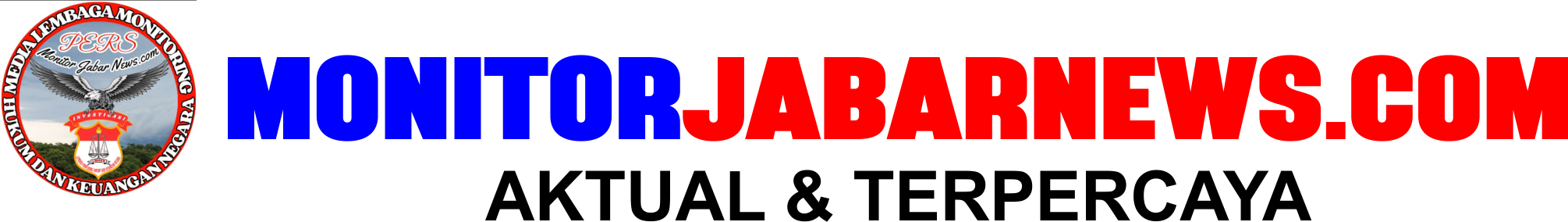Mochdar Soleman, S.IP., M.Si.
Mochdar Soleman, S.IP., M.Si.
Akademisi Universitas Nasional – Sekjen GP Nuku
Dalam tulisan saya sebelumnya, “Banjir Sumatera: Negara yang Absen, Kapital yang Hadir Paling Awal,” saya katakan bahwa bencana yang melanda Sumatera itu bukanlah sebuah kejutan alam, akan tetapi terjadi dari proses panjang perusakan hulu yang dibiarkan tanpa pengawasan. Apa yang sudah saya kemukakan sebelumnya memfokuskan pada bagaimana negara yang kerap terlambat hadir setelah kerusakan terjadi, setelah publik marah, dan setelah kayu-kayu berserakan di sungai sebagai bukti yang menampar muka.
Hal demikian menunjukkan refleksi itu kini menemukan konteks yang lebih tegas, bahwa banjir bandang Sumatera kini tengah memperlihatkan persoalan lingkungan di Indonesia tak lagi berada pada fase peringatan. Kondisi lingkungan Indonesia sudah memasuki fase krisis struktural, di mana negara tidak hanya gagal mengendalikan hulu, melainkan perlahan menyusut dari fungsi paling dasarnya yakni *menjaga keselamatan lingkungan bagi warganya.
Ribuan kayu yang hanyut bukan fenomena alam semata, sebab potongannya rapi, ukurannya seragam, jumlahnya massif “terlalu sistematis untuk disebut sebagai suatu kebetulan belaka.” Kayu-kayu itu adalah potret lingkungan yang ditulis oleh air bah, menceritakan apa yang negara tidak berani ucapkan bahwa hulu Sumatera sudah lama diproduksi sebagai ladang ekstraksi, bukan ruang ekologis.
Ketika banjir menyeret kayu hingga ke hilir, itu berarti ia menyeret pula seluruh kelalaian negara, dalam hal ini dikarenakan izin yang longgar, pembiaran yang kronis, dan serangkaian kompromi yang merusak integritas ekosistem. Setidaknya kondisi ini dilihat sebagaimana bannjir itu datang bukan sekadar membawa air, melainkan ia membawa daftar panjang kegagalan institusional.
Kegagalan tersebut tercermin dari respons negara yang datang setelah kerusakan menjadi tontonan nasional, hal ini terlihat jelas ketika pemerintah bergegas memerintahkan investigasi, memanggil menteri, menggelar rapat darurat. Namun rangkaian tindakan pascabencana tersebut *bukanlah tanda kesigapan.* Ia adalah bukti bahwa negara tidak memiliki mekanisme pencegahan yang hidup, hanya reaksi spontan yang muncul setelah tekanan publik memuncak.
Hal ini tergambar jelas dengan adanya pernyataan resmi yang dikeluarkan bahwa kayu mungkin berasal dari hutan rakyat, pohon tumbang, atau sisa aktivitas lama sebenarnya adalah kalimat-kalimat tanpa data. Ketika lembaga kehutanan tidak dapat memastikan asal kayu di wilayah yang seharusnya diawasi negara, maka masalahnya bukan administrasi melainkan menurut saya sebagai tanda runtuhnya kedaulatan lingkungan.
Dimana dapat kita saksikan bahwa Negara tidak sedang kekurangan informasi, namun negara kehilangan pijakan.
Dalam perspektif politik ekologi, kerusakan hutan tidak pernah terjadi oleh satu pelaku melainkan lahir dari jaringan aktor baik itu perusahaan kayu berizin, operator pembalakan liar, pemilik alat berat, elite lokal, sampai kepada oknum aparat yang merawat celah hukum sebagai ruang ekonomi. Sehingga semua dengan jelas tergambar bergerak secara simultan, saling melengkapi dalam satu sistem ekstraksi yang bekerja jauh sebelum banjir itu datang.
Dari sisi ini, negara menjadi salah satu bagian dari jaringan itu, negara tidak bertindak sebagai pengawas melainkan sebagai pemberi izin dan juga sebagai penyedia legitimasi. Sistem perizinan kerapkali terbuka tanpa pengawasan hanya melahirkan legalitas abu-abu dimana izin yang sah tertera di atas kertas, yang pada akhirnya melahirkan kejahatan lingkungan di lapangan. Ketika kayu-kayu bisa keluar dari hulu tanpa terekam sistem, itu berarti negara tidak mengatur melainkan negara hanya mencatat.
Jika ditinjaui dalam perspektif ekologis, Sumatera telah melewati *titik ambang.* Dengan demikian menyebabkan tutupan hutan menipis hingga kehilangan daya serap. Kondisi dimana tanah tidak lagi memiliki kekuatan mengikat air dan sungai mengalami penyempitan akibat sedimentasi. Kawasan penyangga hilang oleh ekspansi perkebunan dan konsesi kayu. Dalam kondisi seperti ini dapat dijelaskan sebagaimana hujan ekstrem bukanlah ancaman melainkan ia hanya pemantik.
Situasi seperti ini jika dibaca melalui literatur lingkungan global dapat disebut state-enabled disaster *”bencana yang dimungkinkan oleh kebijakan negara.”* Menurut saya istilah itu tepat untuk kondisi Indonesia saat ini.
Namun sangat disayangkan dengan situasi banjir menghantam lintas provinsi, memakan korban jiwa, dan menyingkap kejahatan lingkungan yang masif, namun pemerintah pusat masih ragu untuk menetapkan status menjadi bencana nasional. Ini yang saya sebut sebagai kegamangan yang bukan teknis melainkan ia berwujud politis. Hal ini yang saya sebut, bilamana ditetapkan bencana nasional berarti membuka pintu bagi :
1. Audit total atas konsesi hutan,
2. Penyelidikan terhadap mata rantai pasok kayu,
3. Evaluasi menyeluruh atas izin APL dan PHAT,
4. Hingga identifikasi aktor ekonomi dan politik yang menikmati rente.
Dengan kata lain, jika hal demikian dilakukan sama artinya dengan membuka kemungkinan bahwa negara harus melihat cerminan dari diri sendiri pada cermin kehancuran ekologis.
Saya pikir kondisi ini bagi kita tidak bisa lagi ditoleriri dengan menunggu investigasi yang berakhir sebagai ritual birokrasi. Sehingga menurut saya sudah saatnya kita membutuhkan keberanian politik untuk membenahi hulu sebelum hilir kembali menenggelamkan seluruh wilayah. Sebab menurut saya keberanian untuk mengakui bahwa pembangunan yang meminggirkan lingkungan adalah pembangunan yang membawa bencana sebagai konsekuensi logis.
Negara sudah seharusnya menyadari bahwa banjir kayu Sumatera harus menjadi batas sejarah. Sebab jika negara terus menyusut dari perannya, maka banjir berikutnya hanya menunggu jadwal. Dengan tegas saya katakan bahwa ketika hulu runtuh, hilirlah yang akan terus membayar harga. “Hulu yang retak tidak bisa diperbaiki oleh negara yang tersesat. Sebab bagi saya negara yang tersesat adalah negara yang tak pernah hadir di tempat kerusakan dimulai.”