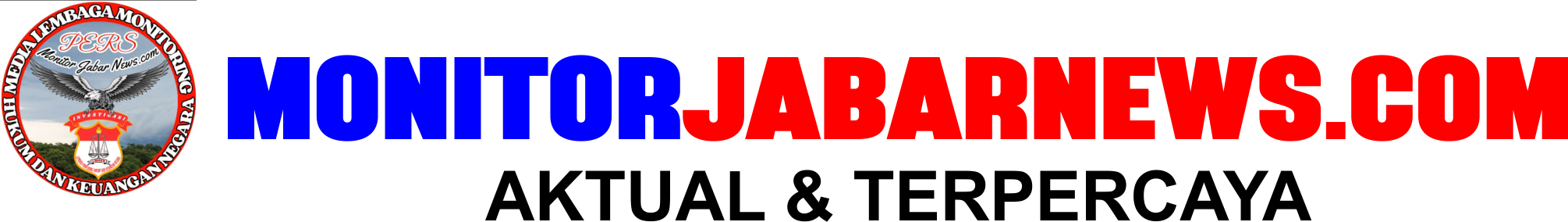DEPOK. Aksi demonstrasi Gerakan Depok Bersatu (GEDOR) di Jalan Siliwangi bukan sekadar peristiwa jalanan. Ia adalah cermin retak yang memantulkan kondisi demokrasi lokal Kota Depok hari ini, riuh pembangunan di permukaan, namun penuh kegelisahan di akar rumput.
DEPOK. Aksi demonstrasi Gerakan Depok Bersatu (GEDOR) di Jalan Siliwangi bukan sekadar peristiwa jalanan. Ia adalah cermin retak yang memantulkan kondisi demokrasi lokal Kota Depok hari ini, riuh pembangunan di permukaan, namun penuh kegelisahan di akar rumput. Di tengah kepungan spanduk, teriakan massa, dan kemacetan yang seolah menjadi latar abadi kota ini, satu pesan terasa paling nyaring: ada jarak yang kian melebar antara pemerintah dan warganya.
Di tengah kepungan spanduk, teriakan massa, dan kemacetan yang seolah menjadi latar abadi kota ini, satu pesan terasa paling nyaring: ada jarak yang kian melebar antara pemerintah dan warganya.
Jalan Siliwangi hari itu tidak hanya menjadi arena protes, tetapi panggung tempat kekecewaan publik menemukan bahasa paling jujurnya. Di antara suara-suara kritis itu, nama Cahyo P. Budiman kembali mencuat. Bukan karena sensasi, melainkan karena konsistensinya menjaga nalar publik agar tidak larut dalam euforia pembangunan yang sering kali kehilangan makna.
Di antara suara-suara kritis itu, nama Cahyo P. Budiman kembali mencuat. Bukan karena sensasi, melainkan karena konsistensinya menjaga nalar publik agar tidak larut dalam euforia pembangunan yang sering kali kehilangan makna.
Cahyo P. Budiman bukan sekadar aktivis. Di Kota Depok, ia telah lama menjadi penanda zaman bahwa demokrasi lokal masih bernapas, meski sering tersengal oleh kekuasaan yang alergi kritik. Ia adalah aktivis senior yang cukup diperhitungkan, bukan karena kegaduhan, melainkan karena keberaniannya mengusik kepalsuan kebijakan publik yang dibungkus rapi oleh jargon-jargon kemajuan.
Hari ini, Depok berdiri di persimpangan penting. Di satu sisi, pemerintah daerah sibuk memamerkan geliat pembangunan: proyek infrastruktur dikebut, narasi kemajuan digaungkan, dan prestasi administratif dikejar seolah menjadi tolok ukur tunggal keberhasilan.
Namun di sisi lain, warga berhadapan dengan realitas yang berlawanan, kemacetan tak kunjung terurai, persoalan sosial berulang, dan isu dugaan korupsi terus muncul tanpa penyelesaian yang memuaskan akal sehat.
Di tengah paradoks inilah, suara Cahyo terdengar “mengganggu”. Tetapi justru gangguan itulah yang dibutuhkan demokrasi.
Demo Gerakan Depok Bersatu atau GEDOR di Jalan Siliwangi bukan aksi spontan. Ia adalah akumulasi panjang rasa tidak didengar. Ketika kanal formal aspirasi terasa buntu, jalanan menjadi ruang terakhir untuk bersuara.
Yang paling menohok dari aksi itu adalah temuan papan segel pemerintah yang justru dibungkus kain. Sebuah adegan simbolik yang telanjang: aturan ada, tetapi tidak ditegakkan. Hukum hadir, tetapi ragu-ragu. Wibawa negara pun tergerus bukan oleh teriakan massa, melainkan oleh inkonsistensi aparatnya sendiri.
Bagi Cahyo, peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran prosedural. Ia adalah pengkhianatan terhadap prinsip negara hukum. Ketika simbol penegakan hukum bisa “dibungkus”, maka yang sesungguhnya dibungkus adalah keadilan dan kepercayaan publik.
Masalah utama banyak pemerintah kota hari ini bukan kekurangan prestasi, melainkan kelebihan pencitraan. Kebijakan dibungkus narasi manis, tetapi miskin keberanian untuk diuji secara terbuka. Kritik sering diperlakukan sebagai ancaman stabilitas, bukan sebagai koreksi yang menyelamatkan.
Cahyo hadir membongkar ilusi tersebut. Ia menyoroti kemacetan yang diwariskan dari satu periode ke periode berikutnya tanpa solusi fundamental. Ia mengkritik pembangunan yang terkesan tergesa-gesa, seolah target politik lebih penting daripada dampak jangka panjang bagi warga.
Pembangunan infrastruktur di Depok kerap dipromosikan sebagai simbol kemajuan. Namun pertanyaan krusial yang jarang dijawab secara jujur adalah, siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung risikonya?
Ketika proyek digerakkan dengan skema pembiayaan yang berpotensi membebani keuangan daerah, publik wajar curiga. Pembangunan semacam ini rawan berubah dari solusi menjadi beban, dari kebijakan publik menjadi proyek kekuasaan. Dalam konteks ini, kritik Cahyo bukan sikap anti-pembangunan, melainkan penolakan terhadap pembangunan tanpa nurani dan akuntabilitas.
Korupsi dan Hukum yang Berhenti di Zona Aman
Isu dugaan korupsi di Depok, termasuk pengadaan lahan pendidikan, memperlihatkan penyakit klasik penegakan hukum, berhenti di level paling aman secara politik. Operator lapangan diproses, sementara aktor intelektual tetap berada di balik tirai kekuasaan.
Cahyo menolak logika ini. Baginya, hukum yang tidak berani menyentuh pusat kendali korupsi adalah hukum yang gagal menjalankan fungsi keadilannya. Di titik ini, kritiknya berubah menjadi tudingan moral: negara hadir setengah-setengah, dan setengah kehadiran itu sama artinya dengan pembiaran.
Yang membedakan Cahyo dari banyak aktivis instan adalah sikapnya terhadap polarisasi politik. Ia tidak menjual kemarahan publik untuk kepentingan kubu tertentu. Ia tidak mengajak warga membenci pemerintah, tetapi mengajak mereka berpikir jernih dan kritis.
Baginya, mendukung kebijakan yang benar dan mengkritik yang keliru adalah kewajiban warga negara, bukan soal oposisi atau loyalitas. Sikap ini membuatnya sulit dikotakkan dan justru itulah yang membuatnya berbahaya bagi kekuasaan yang gemar memelihara pendukung fanatik.
Pertanyaan mendasarnya sederhana namun brutal, apakah Pemerintah Kota Depok siap jujur pada dirinya sendiri? Siap mengakui bahwa tidak semua kebijakan berhasil? Siap mendengar suara yang tidak datang dari lingkar kekuasaan?
Aktivis seperti Cahyo Putranto Budiman bukan musuh pembangunan. Mereka adalah alat uji kejujuran kekuasaan. Jika kritik dianggap ancaman, maka yang sesungguhnya rapuh bukan aktivisnya, melainkan legitimasi pemerintahannya.
Tanpa kritik, kekuasaan akan tumbuh pongah. Tanpa pengawasan warga, pembangunan akan berubah menjadi proyek elitis yang jauh dari rasa keadilan. Maka, jika Depok ingin benar-benar maju, bukan sekadar terlihat maju, suara seperti Cahyo bukan untuk dibungkam, melainkan untuk didengar.
Karena pada akhirnya, demokrasi lokal tidak runtuh oleh kritik keras, melainkan oleh kekuasaan yang menolak bercermin.(AA)